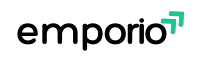Koranriau.co.id-

PERINGATAN Hari Pahlawan Nasional menjadi momentum menegaskan pentingnya mengenang dan meneladani semangat juang para pendahulu bangsa, termasuk perempuan. Namun, Komnas Perempuan menilai jumlah pahlawan nasional perempuan baru sedikit yang diakui negara.
Ketua Komnas Perempuan Maria Ulfa Anshor menyampaikan, dari total 206 pahlawan nasional yang telah ditetapkan pemerintah, hanya 16 orang atau sekitar delapan persen yang merupakan perempuan.
“Angka ini bukan sekadar statistik, melainkan cermin dari konstruksi sejarah yang sering menempatkan perempuan sebagai pendukung, bukan pelaku utama perjuangan bangsa,” ujar Maria dalam webinar peringatan Hari Pahlawan yang digelar Komnas Perempuan, Senin (10/11).
Ia menegaskan, sejarah yang adil gender merupakan fondasi bagi masa depan yang berkeadilan. Karena itu, Komnas Perempuan mendorong agar pengalaman, perjuangan, dan kontribusi perempuan diakui sebagai bagian integral dari sejarah nasional.
Maria menyebut, ada beberapa tokoh perempuan yang dapat diteladani. Antara lain Siti Manggopoh, pejuang asal Sumatera Barat yang memimpin perlawanan terhadap pajak kolonial, Sri Mangunsarkoro, yang memperjuangkan pendidikan bagi perempuan, serta Ida Nasution, aktivis yang berani menyuarakan kritik terhadap kolonialisme dan hilang pada 1944.
“Mereka bukan hanya bagian dari sejarah, tetapi juga penanda moral bangsa,” kata Maria.
Sejarawan Universitas Gadjah Mada, Mutiah Amini menjelaskan bahwa nama-nama seperti Siti Manggopoh menunjukkan betapa banyak pahlawan perempuan yang belum terungkap dalam historiografi Indonesia.
Ia menilai buku-buku sejarah nasional selama ini masih berpusat pada figur laki-laki dan Jawa, sehingga perempuan dari wilayah lain seakan tidak memiliki masa lalu.
“Kalau kita berbicara tentang sejarah, ruangnya selalu laki-laki. Seakan-akan perempuan tidak punya masa lalu. Padahal kemerdekaan dan perjuangan bangsa itu hasil kerja bersama laki-laki dan perempuan,” ujarnya.
Ia menambahkan, masih ada pekerjaan besar untuk menulis ulang sejarah Indonesia agar lebih inklusif terhadap peran perempuan, termasuk melalui pembelajaran sejarah perempuan dan gender di universitas.
Menurut Mutiah, konsep pahlawan juga perlu dikaji ulang agar tidak sekadar menampilkan sosok perempuan yang melawan kolonialisme, tetapi juga mencakup perjuangan perempuan di berbagai konteks sosial, budaya, dan geografis.
“Perempuan itu bukan satu kategori tunggal. Ada perempuan di Jawa, di Agam, di Papua, di Natuna, semuanya punya bentuk perjuangan yang berbeda dan layak diakui,” katanya.
Dalam konteks Siti Manggopoh, Mutiah menilai perjuangan tokoh asal Agam, Sumatera Barat, ini tidak semata tentang pajak kolonial, melainkan juga perlawanan terhadap ketidakadilan sosial dan kultural.
Hidup pada masa 1880 hingga 1965, Siti Manggopoh memimpin perlawanan bersenjata dalam peristiwa yang dikenal sebagai Blasting War dan menjadi satu-satunya perempuan yang memimpin aksi tersebut. Ia kemudian ditangkap dan dipenjara oleh pemerintah kolonial.
“Siti Manggopoh keluar dari zamannya. Ia melakukan perlawanan secara langsung, bukan hanya dari belakang atau dari dapur umum seperti citra yang sering dilekatkan pada perempuan dalam sejarah,” jelasnya.
Ia menambahkan, kesadaran Siti Manggopoh berakar dari sistem sosial Minangkabau yang matrilineal, di mana perempuan memiliki hak atas tanah dan harta warisan keluarga, sehingga kebijakan pajak kolonial yang menekan masyarakat lokal turut mengancam hak-hak perempuan.
Namun, Mutiah menyebut, jejak Siti Manggopoh masih sulit ditemukan dalam arsip formal, namun sempat dimuat dalam majalah Hikmah pada 1960-an melalui wawancara menjelang akhir hayatnya.
Ia berharap penelitian lanjutan, termasuk melalui dokumen pribadi keluarga, dapat dilakukan untuk memperkaya pemahaman tentang tokoh tersebut. (H-4)
Artikel ini merupakan Rangkuman Ulang Dari Berita : https://mediaindonesia.com/humaniora/828910/hari-pahlawan-hanya-8-persen-pahlawan-nasional-perempuan