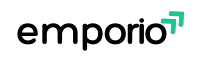Koranriau.co.id-

SESUDAH banjir bandang dan longsor di sejumlah wilayah Sumatra, perhatian publik biasanya bergerak cepat: dari evakuasi, ke distribusi bantuan, lalu ke urusan perbaikan fisik. Pada fase itu bencana tampak seolah mereda. Padahal, di banyak desa, hari-hari pascabencana justru terasa lebih berat: lumpur masih dibersihkan, akses belum sepenuhnya pulih, sebagian keluarga masih berpindah, dan setiap hujan bisa memicu cemas yang sama seperti hari pertama.
Dampaknya pada pendidikan bukan kecil. Pendataan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah per 14 Desember 2025 mencatat 3.274 satuan pendidikan terdampak di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat; dampak langsungnya menyentuh 276.249 peserta didik serta 25.936 guru dan tenaga kependidikan.
Pada saat yang sama, 403.534 peserta didik dari 19.427 rombongan belajar mengalami gangguan layanan pendidikan karena sarana rusak, akses menuju sekolah terputus, warga sekolah mengungsi, dan sebagian sekolah dipakai sementara sebagai posko.
Angka-angka itu bukan sekadar laporan. Di baliknya ada anak yang belum kembali sekolah, ada murid yang lebih sering terlihat di posko atau di pinggir jalan menunggu bantuan, ada buku dan seragam yang hilang, dan ada orangtua yang masih menghitung ulang cara bertahan. Di Sumatra Barat, BNPB bahkan melaporkan situasi anak mengungsi di fasilitas pendidikan, menempati ruang-ruang kelas sekolah yang berubah fungsi menjadi tempat berlindung. Pada kondisi seperti itu, kalimat ‘sekolah segera normal’ terdengar terlalu sederhana karena bagi banyak keluarga, hidup pun belum normal.
ANAK TIDAK HANYA KEHILANGAN KELAS, TETAPI KEHILANGAN RASA AMAN
Bagi anak, bencana bukan sekadar peristiwa alam; bencana merobek rasa aman dan rasa dapat memprediksi hari esok. Anak tidak selalu mampu menyebut takut, sedih, atau bingung dalam kalimat yang rapi. Reaksi sering muncul sebagai perubahan perilaku: mudah tersentak, sulit tidur, melekat pada orangtua, sulit konsentrasi, atau cepat marah. Bukti ilmiah juga menunjukkan keterkaitan paparan bencana pada anak dengan masalah tidur dan gejala stres pascatrauma.
Pada minggu-minggu setelah bencana, rutinitas menjadi obat yang sering diremehkan. Rutinitas yang kembali hadir memberi sinyal kepada anak: dunia masih punya pola, hidup masih bisa diatur, dan masa depan masih mungkin. Karena itu, pemulihan pendidikan tidak seharusnya ditempatkan sebagai ‘urusan nanti’ setelah semua bangunan selesai. Bagi anak, sekolah ialah jangkar psikososial: tempat bertemu teman, bermain, belajar, dan merasa aman dalam struktur yang dikenali.
MENGAPA GURU MENJADI KUNCI DAN MENGAPA GURU JUGA RENTAN
Di titik itulah guru memegang peran yang sangat menentukan. Ketika ruang kelas belum siap, guru sering menjadi pihak pertama yang menghidupkan kembali ‘sekolah’ dalam bentuk paling sederhana: sudut belajar di posko, kelas darurat di balai desa, kegiatan literasi di rumah ibadah, atau pertemuan kelompok kecil di teras rumah warga. Tidak selalu mewah, tetapi konsisten. Anak datang bukan hanya untuk pelajaran, melainkan untuk menemukan kembali rasa normal melalui wajah yang dikenal dan jadwal yang bisa dipegang.
Unicef menegaskan pendidikan dalam situasi darurat tidak hanya menjaga proses belajar, tetapi juga menyediakan ruang belajar yang aman, ramah anak, serta terhubung dengan dukungan perlindungan dan pemulihan psikososial. Dengan kata lain, kelas darurat yang baik tidak sekadar mengejar materi, tetapi juga menata ulang rasa aman agar anak siap belajar lagi.
Namun, ada fakta yang sering luput: guru juga terdampak. Sebagian guru kehilangan rumah, mengalami duka, kesulitan transportasi, atau harus mengurus keluarga yang sama rentannya dengan keluarga murid. Jika guru diminta menjadi pendidik, penguat psikososial, relawan logistik, sekaligus pencatat data bantuan, beban itu bisa berubah menjadi kelelahan yang panjang. Pada akhirnya, yang terancam bukan hanya kesejahteraan guru, melainkan juga kualitas pendampingan anak.
DUKUNGAN UNTUK GURU ADALAH STRATEGI PEMULIHAN, BUKAN TAMBAHAN
Dukungan untuk guru perlu dipahami sebagai strategi inti pemulihan pendidikan di Sumatra. Kabar baiknya, Kemendikdasmen telah menyampaikan penguatan dukungan pendidikan dan guru di wilayah terdampak, termasuk bentuk-bentuk bantuan dan kebijakan dukungan bagi guru dan tenaga kependidikan.
Namun, dukungan paling efektif biasanya bukan satu kebijakan tunggal, melainkan rangkaian dukungan yang saling menguatkan: guru perlu panduan praktis pendampingan psikososial yang mudah dipakai di kelas darurat, perlu materi ajar darurat yang ringan dan kontekstual, perlu perlengkapan belajar minimum agar kelas darurat tidak bergantung pada dana pribadi, dan perlu jalur rujukan yang jelas ketika ditemukan anak dengan tanda stres berat yang menetap.
Dengan dukungan seperti itu, guru dapat fokus pada hal yang paling penting: mengembalikan struktur harian anak, menurunkan kecemasan, dan menjaga keberlanjutan belajar tanpa menambah tekanan. Pembelajaran pun bisa disusun lebih relevan dengan situasi: literasi melalui cerita yang menumbuhkan harapan, matematika sederhana dari pembagian kebutuhan, sains tentang hujan dan aliran air, serta proyek kecil kebersihan dan keselamatan lingkungan. Ini bukan romantisasi bencana, melainkan cara mengembalikan rasa mampu pada anak: pikiran dan keterampilan mereka masih berguna, bahkan saat keadaan belum pulih.
Sekolah yang terdampak ribuan, murid yang terdampak ratusan ribu, dan guru yang terdampak puluhan ribu. Karena itu, ukuran keberhasilan pemulihan di Sumatra tidak cukup dihitung dari bangunan yang berdiri kembali. Ukuran yang lebih jujur ialah ini: berapa banyak anak yang kembali memiliki rutinitas belajar yang aman dan berapa banyak guru yang memiliki dukungan memadai untuk memulihkan kelas sekaligus memulihkan diri mereka. Mendukung guru berarti mempercepat pulihnya anak. Memulihkan anak ialah cara paling masuk akal untuk memastikan Sumatra benar-benar bangkit, bukan sekadar tampak pulih.
Artikel ini merupakan Rangkuman Ulang Dari Berita : https://mediaindonesia.com/opini/843647/sekolah-terdampak-ribuan-mengapa-guru-harus-didukung-dalam-pemulihan