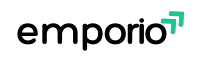Koranriau.co.id-
TELAH menjadi konsensus dalam sistem ketatanegaraan kita bahwa peran aktif negara merupakan kunci untuk membawa kemajuan sosial dan menjamin kepentingan umum. Pada lapangan perekonomian, campur tangan negara juga memiliki mandat yang tidak samar. Hal tersebut dimaksudkan untuk mengatur proses ekonomi secara aktif, baik produksi maupun pembagian hasil produksi. Mencegah pemerasan oleh golongan kuat terhadap golongan lemah dan mengatur agar rakyat secara berangsur-angsur membangun kekuatan produksi sendiri sehingga mereka memperoleh bagian lebih besar dari kue perekonomian.
Begitu pun dalam pengelolaan sumber daya alam. Penguasaan negara atas bumi, air, dan kekayaan alam lainnya merupakan mandat konstitusi yang terang untuk menjamin terwujudnya keadilan sosial. Bahkan lebih dari itu, sumber daya alam harus dapat digunakan sebagai pengungkit untuk membangun fondasi ekonomi domestik yang kuat, serta melepas ketergantungan kepada negara lain. Mempertajam tujuan sebesar-besar kemakmuran rakyat serta membuka jalan bagi perluasan partisipasi rakyat sebagai subjek utama dalam pembangunan yang berkelanjutan.
DUA PARADOKS
Dalam rentang waktu yang panjang, kita telah menyaksikan berlangsungnya dua paradoks dalam pengelolaan kekayaan alam di Indonesia. Paradoks pertama ialah kenyataan bahwa Indonesia memiliki kekayaan alam yang besar, tetapi mayoritas masyarakat, terutama di perdesaan yang menjadi lokus dari kekayaan tersebut, tetap berada dalam pusaran kemiskinan. Daerah-daerah penghasil tambang, perkebunan, perikanan, dan kelautan, meskipun mengalami pertumbuhan ekonomi yang tinggi, punya angka kemiskinan yang sangat besar.
Hal itu terutama banyak disebabkan lebarnya ketimpangan dalam kepemilikan dan akses terhadap sumber daya ekonomi, terutama lahan. Lebih dari 63 juta hektare lahan yang terdiri dari konsesi kehutanan, perkebunan sawit, tambang minerba, dan food estate hanya dimiliki sekitar 3.779 perusahaan besar. Sementara itu, 17.248 juta orang petani guram hanya menguasai 4,3 juta hektare (KPA, 2025).
Data-data ketimpangan di atas bukan sekadar deretan angka, melainkan juga sinyal keras atas defisit keadilan sosial yang dapat memicu beragam konflik sosial. Satu tesis yang semakin relevan dikaji ialah hubungan antara meningkatnya ketimpangan ekonomi dan meluasnya kekerasan dan konflik-konfilk sosial di Indonesia dewasa ini. Semakin timpang, semakin banyak konflik-konflik sosial, yang diisi dengan penggunaan kekerasan oleh pihak yang kuat dan kaya maupun yang lemah dan miskin.
Bagi yang kuat dan kaya, kekerasan merupakan alat untuk menyingkirkan yang lemah dan miskin. Sebaliknya bagi yang lemah dan miskin, kekerasan merupakan penyaluran agresi sebagai akibat rasa frustrasi. Indikatornya dapat dilihat dari catatan Konsorsium Pembaruan Agraria atas rentetan konflik berdimensi sumber daya alam (konflik agraria) yang meningkat 21% sepanjang 2024 di Indonesia.
Paradoks lainnya berpusat pada persoalan paradigmatik. Dominasi pemikiran yang memandang bahwa kekayaan alam (terutama yang tidak terbarukan) merupakan objek dari eksploitasi untuk melayani pertumbuhan ekonomi tinggi. Pendekatan itu terbukti gagal jika melihat pengalaman pahit dan panjang praktik pengisapan kekayaan alam Indonesia oleh negara lain sejak masa kolonialisme. Model pembangunan yang sarat paktik perburuan rente, serta menyebabkan ketertinggalan Indonesia dalam membangun fondasi industri nasional yang kuat berbasis sumber daya alam.
Paradigma ekonomi ekstraktif abad ke-20 tersebut semakin tidak relevan bahkan dianggap sudah kadaluwarsa. Dalam cara pandang baru, tujuan pembangunan ekonomi harus dialihkan dari hanya fokus pada pertumbuhan ekonomi tanpa henti menjadi penciptaan kesejahteraan manusia dan kelestarian lingkungan. Seluruh operasi perekonomian harus ditempatkan dalam cara pandang melihat lingkungan alam yang terbatas sehingga menuntut penghormatan atas batasan ekologisnya. Narasi baru ekonomi masa kini ialah memperkuat model-model ekonomi berkelanjutan yang memosisikan peran negara, pasar, dan masyarakat secara lebih tepat. Ujungnya ialah memastikan agar manfaat ekonomi terdistribusi secara adil dan merata kepada semua orang.
REFORMASI TATA KELOLA
Satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, penguatan narasi pembangunan yang bersandar pada konstitusi semakin lantang resonansinya. Presiden Prabowo Subianto di berbagai kesempatan gencar mendorong pentingnya menjalankan kebijakan pembangunan yang senapas dengan Pasal 33 UUD 1945, terutama dalam pengelolaan sumber daya alam yang berpihak pada ekonomi rakyat dan kepentingan nasional. Komitmen itu harus dipahami sebagai arahan Presiden, khususnya kepada Menteri ESDM untuk melakukan koreksi fundamental tata kelola SDA, khususnya untuk mewujudkan kemandirian energi dan percepatan hilirisasi. Itu kedua agenda yang terlalu penting untuk sekadar diwacanakan, tetapi membutuhkan nyali untuk mengeksekusi di lapangan.
Terdapat perkembangan penting yang dapat menjadi rujukan awal bagaimana pemerintah sedang mengarah ke perbaikan tata kelola sumber daya alam, khususnya di bidang energi dan pertambangan mineral yang lebih mandiri dan berkeadilan. Hal tersebut setidaknya dapat dilihat dari tiga agenda berikut.
Pertama, penguatan kemandirian dan ketahanan energi nasional melalui pembangunan 18 fasilitas penyimpanan minyak (oil storage) dan kilang minyak (oil refinery), masing-masing berkapasitas 1,7 juta barel dan 60 ribu barel per hari. Pembangunan oil storage memiliki peran strategis untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap terminal BBM regional di Singapura yang rentan terhadap gejolak pasar dan krisis pasokan global.
Penyediaan infrastruktur penyimpanan domestik menjadi instrumen penting untuk mendukung optimalisasi kilang nasional, membangun cadangan strategis energi (strategic petroleum reserves), dan sistem distribusi BBM yang lebih tangguh dan menjangkau wilayah kepulauan. Pada pembangunan kilang minyak, langkah itu harus ditempatkan sebagai strategi nasional swasembada energi dan memperkuat ketahanan energi dalam jangka panjang.
Bagaimanapun, migas masih menjadi sumber energi fosil yang diandalkan dunia. Selama periode 1965-2023, migas memasok rata-rata 63% suplai energi global, bahkan diperkirakan masih akan terus memasok permintaan energi dunia sebesar 44% pada 2050 (Syeirazi, 2025). Membangun ketangguhan bangsa pada penyimpanan dan kilang akan mengurangi ketergantungan Indonesia pada impor produk BBM yang membebani neraca perdagangan dan subsidi energi. Kebijakan itu harus dibarengi dengan perbaikan tata kelola serta membangun institusi yang kuat untuk mengurangi risiko kutukan dari sektor itu yang telah merusak Indonesia pada masa sebelumnya.
Kedua, percepatan agenda hilirisasi sumber daya alam melalui 16 inisiasi proyek prioritas di sektor minerba, transisi energi, pertanian, kelautan dan perikanan. Hilirisasi sumber daya alam menjadi kunci transformasi ekonomi Indonesia menuju struktur industri bernilai tambah tinggi. Itu merupakan jalan kebangsaan yang wajib ditempuh dan agenda politik kemakmuran yang lebih luas.
Untuk menjalankan industrialisasi, diperlukan mesin-mesin, teknologi, serta pengetahuan yang lebih kompleks di bidang pengolahan bahan baku. Semua kebutuhan itu akan menciptakan jenis-jenis lapangan kerja baru yang lebih luas serta mendorong inovasi untuk menjawab beragam tantangan peradaban manusia modern saat ini.
Hilirisasi tembaga menjadi katoda tembaga, misalnya, memiliki peran strategis dalam agenda transisi energi global. Hampir seluruh pembangunan infrastrukur energi terbarukan, seperti pembangkit listrik dan jaringan transmisi, termasuk juga elektronik membutuhkan tembaga dalam jumlah besar. Hal serupa dapat terjadi pada usul proyek hilirisasi komoditas silika dan bauksit yang akan diproses menjadi panel surya. Jika dilaksanakan, proyek itu dapat memperkuat ketahanan energi nasional dan menciptakan ekosistem industri energi surya domestik yang berdaya saing global, selain mengurangi ketergantungan terhadap impor solar cell dan wafer dari Tiongkok.
Hilirisasi mineral untuk mendukung transisi energi itu tidaksaja penting, tetapi juga merupakan langkah sistematis dekolonialisasi atas agenda transisi energi di Indonesia, yang sering kali dalam praktiknya bermuara pada tiga hal: belanja kebijakan melalui utang, membiayai proyek-proyek transisi energi dengan utang, dan memfasilitasi impor pembelian teknologi dari negara lain.
Ketiga, legalisasi sumur rakyat dan memperluas akses pengelolaan pertambangan bagi UKM, koperasi, dan BUMD. Kebijakan itu memapankan sebuah pendekatan baru untuk mendemokratisasikan pengelolaan sumber daya alam, melalui perluasan partisipasi rakyat dan daerah di dalamnya. Terdapat 45 ribu sumur rakyat yang akan dilegalisasi dan ditata sehingga memberikan manfaat ekonomi dan meningkatkan keselamatan kerja dan memenuhi standar lingkungan. Meski demikian, kebijakan itu tetap membutuhkan keterlibatan aktif pemerintah, pemerintah daerah, BUMD, dan SKK Migas untuk memberikan bimbingan teknis kepada para penambang sumur rakyat.
TANTANGAN
Dalam perspektif ekonomi-politik, tantangan pada implementasi ketiga agenda strategis di atas setidaknya dapat dipetakan menjadi tiga hal berikut. Pertama, kemampuan pemerintah, terutama Presiden dan Menteri ESDM, untuk mencegah ‘pembonceng’ yang memanfaatkan kebijakan untuk keuntungan diri sendiri dan kelompoknya, serta memapankan kembali bangunan oligarki dalam struktur penguasaan sumber daya alam. Penataan tata kelola SDA harus steril dari konflik kepentingan yang akan merusak kepercayaan rakyat atas komitmen untuk menapaki jalan baru yang diyakini pemerintah saat ini.
Kedua, mengatasi rintangan politik dalam operasi pemerintah. Hal itu disebabkan gagalnya komunikasi dan negosiasi terhadap kekuatan politik di luar pemerintahan serta ketidakmampuan aparat birokrasi dalam mengeksekusi kebijakan. Mengingat peta kekuatan koalisi parpol pendukung pemerintah saat ini, Prabowo mungkin akan mendapatkan dukungan yang solid atas agenda yang akan dilaksanakan. Rintangan terbesar dapat terjadi karena lemahnya dukungan teknokratis aparat birokrasi dalam merespons agenda-agenda reformasi yang sedang dijalankan.
Jika pemerintah hendak mengejar tujuan strategis pembangunan melalui campur tangan negara dalam pengelolaan sumber daya alam, hal tersebut mensyaratkan tersedianya perangkat birokrasi yang mumpuni. Mereka merupakan individu yang cakap dan mengerti atas soal-soal penting yang sedang dihadapi, serta bertindak cepat untuk menterjemahkan dan mengeksekusinya di lapangan. Di atas segalanya, mereka juga harus jujur dan berpikiran terbuka.
Last but not least ialah soliditas dan persatuan nasional untuk mengantisipasi reaksi yang muncul dari kekuatan-kekuatan modal yang terusik dan terancam dengan kebijakan baru. Mereka bisa berasal dari individu atau kelompok, baik di dalam maupun luar negeri, yang diuntungkan karena kelonggaran-kelonggaran yang diberikan selama ini dalam kebijakan perdagangan, investasi, atau penguasaan sumber daya ekonomi.
Cara pemerintah menyikapi hal itu menjadi kunci karena dapat tergelincir mengambil pilihan yang mengarah ke pembatasan demokrasi ketimbang fokus pada tujuan dan mengambil hati rakyat untuk mendukung agenda reformasi yang dijalankan. Wallahualam.
Artikel ini merupakan Rangkuman Ulang Dari Berita : https://mediaindonesia.com/opini/833961/jalan-baru-tata-kelola-energi-dan-mineral