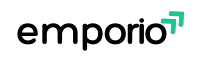Koranriau.co.id-
PARTAI politik di DPR begitu reaktif dalam merespons Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 135/PUU-XXII/2025. Hanya, reaksi yang menonjol tidak diarahkan untuk membahas substansi dan ide yang disampaikan dalam putusan MK tentang format keserentakan pemilu. Hanya berselang sepekan dari MK membacakan putusan, DPR justru merespons akan melakukan revisi terhadap UU MK.
Yang lebih mengejutkan lagi, materi revisi justru mengutak-atik lagi periodesasi masa jabatan hakim MK. Materi yang ‘baru saja’ pada 2020 lalu direvisi oleh DPR dan presiden. Tanpa bermaksud untuk menimbulkan tendensi kepada DPR, mahfum bagi banyak orang, ini adalah bentuk ‘garukan’ DPR terhadap MK. Beberapa partai politik di DPR berang karena MK memutus format keserentakan pemilu yang tidak sesuai dengan selera DPR.
Kalau membuka kembali gagasan hukum responsif yang dikembangkan oleh Philipe Nonet dan Philip Selznick dalam buku Law and Sciety in Transition: Toward Responsie Law, hukum mestinya dibentuk sebagai respons atas kebutuhan aktual dan sosial masyarakat. Bukan reaksi kemarahan atas lembaga peradilan yang putusannya dianggap tidak meguntungkan sebagian kelompok yang ada di lembaga legislasi. Hukum tidak boleh menjadi alat represi dari pemegang kekuasaan. Hukum mesti menjawab konteks sosial yang berubah. Orientasi terhadap pemecahan masalah ialah fondasi penting bagi para pembentuk hukum (Nonet & Selznick: 1978).
TAFSIR PEMILU SERENTAK
Putusan MK No 135/PUU-XII/2024 yang menafsirkan format keserentakan pemilu lahir dari kesadaran bahwa pilihan terhadap keserentakkan pemilu adalah hal yang sangat mendasar di dalam penyelenggaraan pemilu. Perkembangan paling mutakhir yang dijawab oleh MK di dalam putusan ini adalah pilihan keserentakan pemilu merupakan aspek yang berdampak langsung terhadap pemenuhan asas pemilu yang diatur di dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945.
Dengan kondisi ini, tentu saja format keserentakan pemilu bukan lagi menjadi masalah implementasi UU atau merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk UU (open legal policy). Namun, pilihan model keserentakan pemilu ialah masalah konstitusionalitas norma yang mesti djawab dan diputus oleh MK. Bagian inilah yang tak terbaca dan diabaikan oleh banyak pihak.
Menurut MK, model keserentakan pemilu lima kotak (presiden, DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota) pada waktu yang bersamaan telah secara faktual menyulitkan tiga aktor utama pemilu: pemilih, penyelenggara, dan peserta pemilu. Kesulitan yang dialami pemilih, penyelenggara, dan peserta pemilu itu sudah berdampak pada pemenuhan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil di dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia.
Pengalaman Pemilu 2019 dan 2024 telah meyakinkan MK bahwa kondisi aktual penyelenggaraan pemilu membuat MK mesti memperdalam tafsirnya terhadap format keserentakan pemilu. Penyelenggara pemilu, khususnya KPU, semakin keteteran mengelola tahapan pemilu lima kotak sekaligus. Manajemen penyelenggaraan pemilu berantakan. Hampir seluruh tahapan pemilu bermasalah. Mulai verifikasi partai, pencalonan, kampanye, pungut hitung, sampai proses rekapitulasi suara.
Kondisi buruk itu semakin terlihat ketika pemilu serentak lima kotak dihimpitkan tahapannya dengan pilkada serentak di seluruh wilayah Indonesia pada 2024. Salah satu contoh saja, pada Pemilu 2024 yang lalu, KPU kabupaten/kota mesti melaksanakan pendaftaran pemilih untuk Pilkada 2024, tapi di saat yang bersamaan mesti mempertanggungjawabkan hasil Pemilu 2024 pada forum penyelesaian perselisihan hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi.
Pemilih pun menghadapi persoalan yang jauh lebih serius. Kualitas representasi pemilih semakin menurun jika dihadapkan pada pemilu serentak lima kotak. Suara pemilih yang tidak sah terus tinggi. Salah satu musabab keadaan ini ialah pemilih bingung dihadapkan pada lima surat suara sekaligus.
Belum lagi jumlah calon anggota legislatif per partai yang mesti disigi oleh pemilih. Bahkan, pada Pemilu dan Pilkada 2024 terpampang fenomena krusial lainnya: partisipasi pemilih dalam pilkada turun drastis karena jenuh dihadapkan pada perhelatan pemilu dua kali dalam jarak waktu yang sangat sempit.
Peserta pemilu, jika hendak jujur, sesungguhnya menghadapi persoalan yang jauh lebih pelik. Salah satu yang dapat dilihat secara terang benderang ialah kelelahan partai politik melakukan rekrutmen politik dalam satu momen yang sama untuk tiga layer pemilu legislatif sekaligus. Partai politik menghadapi situasi yang sangat sulit, ketika mesti ‘merekrut’ caleg untuk pemilu DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota pada satu waktu yang bersamaan.
Kalaupun bisa dilakukan, partai politik pada akhirnya masih sangat jauh dari menghadirkan calon anggota legislatif yang memiliki asosiasi nilai kepartaian yang kuat dan solid. Contoh terbaru tentu saja bagaimana partai politik ‘menghindari’ untuk memenuhi kuota 30% perempuan di dalam daftar caleg di setiap daerah pemilihan pada Pemilu 2024 yang lalu. Pangkal persoalannya tentu saja waktu yang sangat kasip di dalam melakukan rekrutmen politik dan konsolidasi organisasi.
Sengkarut persoalan pemilu yang dihadapi oleh pemilih, peserta, dan penyelenggara pemilu tentu tidak boleh dibiarkan terus-menerus. Penyelenggaraan pemilu tidak bisa lagi hanya menjadi rutinitas lima tahunan, menghasilkan pejabat politik, lalu selesai. Namun, kualitas penyelenggaraan pemilu, nilai kedaulatan rakyat mesti ditingkatkan. Salah satu hulu dari persoalan ini ialah format keserentakan pemilu. Oleh sebab itulah, putusan MK tentang format keserentakan pemilu ini mestinya jadi pemantik bagi anggota DPR, termasuk presiden, untuk segera membahas revisi UU Pemilu dan Pilkada.
Reaksi menolak putusan MK, lalu menarik putusan MK menjadi bola liar ialah sikap yang tidak tepat. Putusan MK justru telah memberikan batasan konstitusional (constitutional boundary) bagi pembentuk undang-undang di dalam menata format keserentakan pemilu. Satu perdebatan yang berpotensi berlarut-larut di DPR sudah diberikan batasan oleh MK. Bahwa dari 2029, pemilu serentak terbagi atas dua: pemilu presiden, DPR, dan DPD dilaksanakan secara serentak, lalu dua tahun atau dua setengah tahun setelah pelantikan presiden atau pelantikan DPR, tahapan pemilu DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota serentak dengan pemilihan kepala daerah bisa dimulai.
Memaknai putusan MK soal keserentakan pemilu itu memang tidak bisa hanya membenturkan masa transisi pemisahan pemilu DPR dengan pemilu DPRD. Apalagi membelokkan putusan MK dengan makna bahwa pemilu DPRD tidak lagi dilaksanakan satu kali dalam setiap lima tahun. Sama sekali tidak ada di dalam Putusan MK No 135/PUU-XXII/2025 yang mengatakan bahwa pemilu DPRD tidak lagi dilaksanakan lima tahun sekali. Aspek yang ditafsirkan oleh MK ialah jadwal pelaksanaan pemilu DPR tidak bisa lagi dilaksanakan bersamaan dengan pemilu DPRD. Terkait dengan masa jabatan anggota DPRD dan pelaksanaan pemilunya tetap dilaksanakan dalam siklus lima tahun sekali.
Tafsir MK yang memerintahkan pemisahan pemilu DPR dengan pemilu DPRD memang akan berkonsekuensi pada masa transisi waktu pelaksanaan pemilu DPRD dan kepala daerah. Masa transisi ialah sesuatu yang sah secara hukum sepanjang diatur di dalam undang-undang dan tidak merugikan subjek hukum yang paling terdampak dari masa transisi itu.
Oleh sebab itu, transisi waktu pemilu DPRD dan pemilihan kepala daerah perlu untuk dirumuskan secara matang. Opsi yang tersedia cukup banyak. Pilihan pertama bisa memperpanjang masa jabatan anggota DPRD hasil Pemilu 2024 sampai 2031. Pilihan yang lainnya, pemilu DPRD pada 2029 tetap dilaksanakan, tapi masa jabatannya hanya sampai 2031. Formulasi yang lain tentu juga tersedia. Kuncinya ialah pembentuk undang-undang mesti segera membahas revisi UU Pemilu agar seluruh pilihan dibincangkan di dalam kerangka kebijakan hukum.
ESENSI JUDICIAL REVIEW
Beberapa anggota DPR menyampaikan penolakan terhadap putusan MK karena menganggap MK menjadi pembuat norma atau sebagai positif legislator. Pendapat itu tentu agak sedikit menggelikan. Argumentasi menolak putusan MK karena menganggap MK menjadi pembentuk norma ialah pendapat yang sangat lemah dari segi konsep. Bahkan, pendapat tersebut menunjukkan sikap ahistoris terhadap lahirnya konsepsi judicial review pada 1803 di Amerika Serikat serta lahirnya lembaga Mahkamah Konstitusi di beberapa negara, termasuk di Indonesia.
Dalam konsep judicial review, putusan MK memang hampir bisa dipastikan akan melahirkan norma baru. Sebab, dalam kewenangan menguji dan menafsirkan konstitusi, Mahkamah memang diberikan kewenangan menafsirkan norma yang sesuai dengan nilai yang terkandung oleh konstitusi.
Hasil penafsiran dari Mahkamah itu ialah tafisir terhadap nilai-nilai di dalam sebuah konstitusi. Artinya, tafsir MK tidak hanya akan merujuk teks-teks di dalam konstitusi, tetapi juga merujuk kepada berbagai macam metode penafsiran hukum lainnya karena kita sadar bahwa mengubah teks konstitusi tiap sebentar sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman hampir tidak mungkin bisa dilakukan. Apalagi dalam sistem perubahan konstitusi, kita yang terbilang sangat rigid, ongkos politik dan ekonomi yang mesti dibayar akan sangat mahal.
Atas kondisi itulah peranan MK di dalam menafsirkan hukum diberikan oleh konstitusi. Mahkamah Konstitusi punya peranan memastikan setiap norma UU tidak merugikan hak konstitusional warga negara. Selain itu, putusan MK menjadi ruang untuk menjawab kebutuhan konsep konstitusi yang hidup sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan ketatanegaraan yang acap kali berubah dengan cepat. Apalagi dalam sejarah MK berdiri sejak 2003 sudah tak terbilang putusan MK yang membuat norma baru dalam otoritas MK sebagai pelindung dan penafsir konstitusi.
Oleh sebab itu, ketimbang menyiapkan revisi UU MK, energi DPR dan Presiden sebagai pembentuk UU lebih baik diarahkan untuk melakukan assesment terhadap praktik Pemilu serentak 2019 dan 2024. Itu jauh lebih dibutuhkan menjadi prioritas legislasi parlemen saat ini.
Kembali merujuk pada esensi politik hukum yang disampaikan oleh Nonet dan Selznick, politik hukum hendaknya dibutuhkan untuk menjawab fenomena sosial dan menjawab kebutuhan masyarakat. Bukan untuk menjadi ajang pamer kekuasaan para pembentuk UU. Apalagi dalam konteks ini, UU MK direvisi karena kemarahan DPR atas putusan MK. Suatu sikap yang akan semakin menjauhkan dari prinsip negara demokrasi konstitusional.
Artikel ini merupakan Rangkuman Ulang Dari Berita : https://mediaindonesia.com/opini/794020/menata-pemilu-serentak-bukan-menggaruk-mk