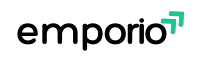Koranriau.co.id – 
Jakarta, CNN Indonesia —
Ombudsman RI menemukan ketidaksesuaian antara kontrak dan realisasi dalam penyediaan bahan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Di Bogor, misalnya, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) alias dapur umum MBG menerima beras medium dengan kadar patah di atas 15 persen, meskipun kontrak jelas mencantumkan beras premium.
Kepala Keasistenan Pencegahan Maladministrasi KU III Ombudsman RI Kusharyanto menyebut temuan tersebut sebagai bentuk penyimpangan prosedur.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Yang kami temukan itu adalah bahwa ada penyimpangan ketika pengadaan menyatakan premium tetapi yang disediakan oleh supplier justru medium, dan itu lolos dari pengecekan SPPG. Kalau anggaran yang dibelanjakan untuk premium, semestinya memperoleh bahan baku sesuai kontrak,” ujarnya dalam konferensi pers di Gedung Ombudsman RI, Jakarta Selatan, Selasa (30/9).
Menurut Kusharyanto, kasus ini terjadi karena kelalaian dalam verifikasi mutu bahan. Kontrak yang seharusnya menjadi pegangan justru disimpangi, sementara SPPG tidak cukup teliti dalam memastikan kualitas.
Akibatnya, negara membayar dengan harga premium tetapi anak-anak di sekolah hanya menerima beras dengan kualitas medium, yang pada akhirnya mempengaruhi kualitas sajian MBG itu sendiri.
“Negara membayar dengan harga premium, sementara kualitas yang diterima anak-anak belum optimal,” ujar Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika dalam kesempatan yang sama.
Temuan itu menjadi bagian dari kajian Ombudsman terkait penyelenggaraan MBG yang masih menyimpan banyak catatan.
Di beberapa dapur, misalnya, sayuran diterima dalam kondisi tidak segar dan lauk-pauk datang tidak lengkap. Situasi tersebut terjadi karena belum adanya standar (AQL) yang tegas.
Persoalan lain juga muncul sejak proses penetapan mitra yayasan dan SPPG. Dari 60.500 yayasan yang mendaftar, Ombudsman mencatat masih ada 9.632 yayasan menunggu kepastian karena ketiadaan standar waktu pelayanan.
Yeka menyebut kondisi ini bukan hanya menimbulkan ketidakpastian hukum, tapi juga membuka potensi afiliasi yayasan dengan jejaring politik yang berisiko menimbulkan konflik kepentingan serta penyalahgunaan wewenang.
“Kajian Ombudsman mengidentifikasi potensi afiliasi sejumlah yayasan dengan jejaring politik. Situasi ini menjadi pengingat bahwa pengelolaan program berskala nasional harus dijalankan secara transparan, adil, dan bebas dari intervensi politik agar kepercayaan publik terjaga,” tutur Yeka.
Di lapangan, keterbatasan sumber daya manusia (SDM) juga menjadi tantangan. Di Bogor, staf inti SPPG seperti ahli gizi dan akuntan dijanjikan honorarium Rp5 juta per bulan, tetapi realisasinya baru cair setelah tiga bulan.
Kondisi ini berpengaruh pada motivasi kerja. Di Garut dan Bandung Barat, relawan yang jumlahnya sekitar 50 orang per SPPG mengeluhkan beban kerja berat mulai dari dapur hingga distribusi yang tak sebanding dengan kompensasi.
Sementara di Lebong, Bengkulu, serta Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah, guru terpaksa merangkap sebagai penanggung jawab distribusi tanpa dukungan tambahan.
Situasi serupa juga ditemukan di Bangka Belitung, di mana guru harus mengatur distribusi makanan tanpa insentif maupun fasilitas yang memadai.
Menurut Yeka, hal ini menunjukkan bahwa persoalan SDM bukan hanya soal jumlah, tetapi juga menyangkut penataan peran, beban kerja, serta mekanisme kompensasi yang adil.
Masalah turut berlanjut dalam tahap pengolahan makanan. Standar hazard analysis and critical control point (HACCP) belum konsisten dijalankan.
Sejumlah dapur tidak memiliki catatan suhu maupun retained sample sebagai bagian dari sistem pengendalian mutu. Padahal, keterlibatan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam 13 item pengawasan semestinya aktif dan menyeluruh.
“Fakta adanya 17 kejadian luar biasa (KLB) keracunan hingga Mei 2025 menjadi pengingat bahwa SOP pengolahan harus diperbaiki dan ditegakkan lebih disiplin,” ujar Yeka.
Distribusi sebagai ujung rantai layanan juga tak luput dari masalah. Standar holding time empat jam yang ditetapkan untuk menjaga keamanan pangan kerap dilanggar.
Di Bangka Belitung, distribusi bahkan sempat terhenti dua minggu tanpa pemberitahuan memadai.
Guru kembali menjadi tumpuan distribusi, meski tanpa dukungan tambahan. Yeka menyebut situasi ini memperlihatkan perlunya tata kelola distribusi yang lebih setara, transparan, dan berpihak pada penerima manfaat.
Sistem pengawasan MBG pun masih parsial. Yeka mencatat dashboard digital Badan Gizi Nasional (BGN) belum mampu menampilkan data real time terkait mutu bahan, jadwal distribusi, maupun insiden keracunan.
Selain itu, skema ad cost belum memiliki petunjuk teknis rinci, sehingga membuka ruang ketidakpastian dalam penggunaan dana.
“Dashboard digital BGN, misalnya, belum mampu menampilkan secara real time data terkait mutu, bahan, jadwal distribusi, maupun insiden keracunan. Skema ad cost yang belum memiliki juknis rinci juga membuka ruang ketidakpastian dalam penggunaan dana,” tutur Yeka lebih lanjut.
(del/sfr)
Artikel ini merupakan Rangkuman Ulang Dari Berita : https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20250930200057-92-1279472/ombudsman-sebut-mbg-di-bogor-pakai-beras-medium-padahal-wajib-premium